Dunia sepak bola Indonesia kembali berduka. Kali ini, seorang pemuda Bandung harus kembali meregang nyawa sekembalinya ia dari pertandingan sepak bola. Ricko Andrean menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Santo Yusup Bandung akibat luka yang diterimanya ketika ia menyaksikan “Big Match” antara Persib melawan Persija. Ricko adalah seorang Bobotoh tulen. Ia kerap kali meninggalkan pekerjaannya untuk menyaksikan tim kesayangannya bertanding. Nahas, dalam pertandingan itu Ricko menyaksikan pemandangan brutal yang baginya tidak pantas oleh dilakukan sesama manusia. Sekelompok Bobotoh nampak menghajar orang yang dicurigai sebagai Jakmania -pendukung Persija Jakarta. Ricko pun dengan inisiatif melindungi Jakmania tersebut sebagai sesama manusia. Namun takdir berkata laim. Ricko yang hari itu tidak memakai penyiri identitasnya sebagai Bobotoh malah dituduh sebagai seorang Jakmania. Dia dihajar tanpa ampun.
Ricko lalu dibawa ke rumah sakit AMC Cileunyi, namun karena kondisinya yang cukup parah, ia dibawa langsung ke Rumah Sakit Santo Yusup. Di sana, Ricko menjadi pusat perhatian. Ada banyak tokoh masyarakat yang hadir menjenguk dan memberi santunan kepada Ricko, mulai dari walikota Bandung Ridwan Kamil, pemain Persib Kim Jeffrey dan Atep, manajer Persib Wak Haji Umuh Muchtar, ketua kelompok bobotoh terbesar Viking Heru Joko, hingga ketua Jakmania Ferry Indra Syarif. Dua nama terakhir datang bak isyarat untuk sebuah kejadian yang sebenarnya sudah sangat ditunggu insan sepak bola Indonesia terutama Bandung dan Jakarta: perdamaian antara Bobotoh dan Jakmania.
Bobotoh dan Jakmania sebenarnya bukanlah entitas yang bisa disejajarkan. Bobotoh adalah penggemar Persib pada umumnya, mereka cair dan tidak terikat pada organisasi apapun kecuali Persib. Tidak perlu kartu anggota untuk menjadi seoramg Bobotoh. Sedang Jakmania adalah wadah untuk para penggemar Persija. Ini masih bisa diperdebatkan, namun saya rasa, nama Jakmania sendiri sudah bergeser dan memiliki konteks yang nyaris mirip dengan Bobotoh.
Rivalitas Persib dan Persija sebenarnya sebuah rivalitas yang dapat dikatakan “lucu.” Seringkali laga ini diberi embel-embel seperti “El Clasico”-nya Indonesia atau Indonesian Derby, dan lain-lain. Tak jarang para komentator yang entah sedang mabuk apa membandingkan rivalitas ini dengan Madrid vs Barcelona atau Celtic vs Rangers. Tanpa latar belakang sejarah yang kental, Madrid yang mewakili Bangsa Spanyol dan Barcelona yang mewakili bangsa Katalan, atau Celtic yang mewakili kaum Protestan dan Rangers yang mewakili kaum Katolik. Orang Bandung dan Orang Jakarta, tidak pernah punya masalah yang berkaitan dengan identitas masing-masing. Sunda dan Betawi damai, tidak pernah ribut bahkan dalam sejarah panjang keduanya.
Rivalitas kedua klub ini diawali oleh fans juga. Awalnya, Jakmania ditolak masuk ke Stadion Siliwangi karena pada waktu itu Siliwangi sudah penuh. Entah kenapa, Jakmania yang datang dengan damai malah dilempari. Dimulailah rivalitas yang tidak sehat di antara dua suporter ini. Sayangnya, rivalitas ini dipelihara, namun disebarkan dengan cara yang tidak baik. Ribut antar suporter sudah menjadi hal yang dianggap biasa bahkan malah dianggap membanggakan. Coba saja cari screenshot di mana baik Bobotoh maupun Jakmania dengan bangga membagikan “karya agung” mereka yang berlumuran darah, dengan judul “mati kau Vikjing/Jaknjing/Bobodoh/dan istilah merendahkan lainnya”. Menjijikan. Saya tidak menyarankan anda-anda untuk mencarinya.
Ini tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa bisa mereka bisa sampai sebegitunya ? Tentu banyak sekali faktor yang bisa dikaitkan dengan kasus ini. Namun, saya tertarik dengan sebuah kutipan dari seorang penulis berkebangsaan India, yang merupakan seorang ahli poskolonialisme. Namanya Gayatri Spivak. Kutipannya sendiri saya dapat dari seorang penulis berkebangsaan Prancis yang bernama Laurent Binet. Binnet adalah seorang penulis novel yang tertarik dengan tema Perang Dunia Kedua. Novelnya yang berjudul HHhH adalah salah satu buku favorit saya. Binet mengutip Gayatri Spivak yang menyatakan bahwa: “saya membenci identitas. Tidak ada konsep yang lebih membahayakan daripada ini.”
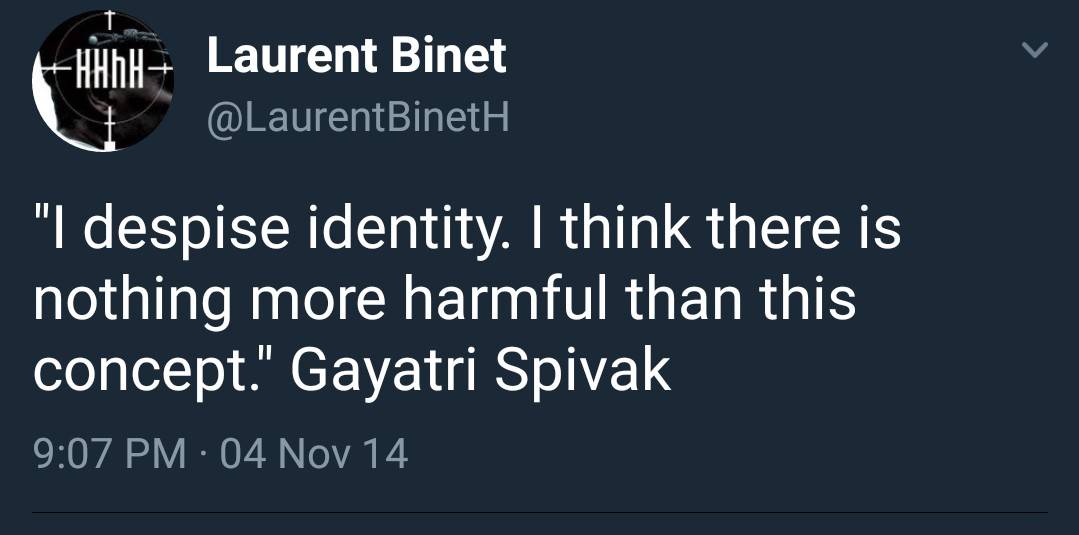
Baik Spivak maupun Binet tentu sangat akrab dengan konsep identitas. Poskolonialisme adalah sebuah pandangan yang menjadikan identitas sebagai inti utama pembicaraan mereka, sedangkan Binet yang membahas Perang Dunia II tentunya paham betul bagaimana identitas adalah salah satu bahan bakar utama dalam kobaran api kebencian semasa perang.
Identitas adalah sebuah konsep yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seseorang. Ia melekat kepada diri seseorang. Suku, Agama, Ras, Klub Sepak Bola Kesukaan, bahkan hingga warna mobil kesayangan pun dapat menjadi sebuah identitas yang melekat pada diri seseorang. Pada masa ini, tidak bisa dipungkiri kalau identitas adalah salah satu hal penting yang dirasa wajib dimiliki seorang manusia.
Saya tidak mengelak bahwa saya pun memiliki identitas dan cukup bangga dengan identitas tersebut, entah itu yang diberikan oleh Tuhan, maupun yang saya pilih sendiri. Tuhan memilih saya untuk lahir di Bandung dari pasangan orang Sunda. Itu membuat saya menjadi orang Bandung sekaligus orang Sunda. Bangga ? Lumayan. Siapa sih yang tidak mau bangga dengan diri sendiri ? Kalau ditanya, di mana ingin tinggal, tentu jawabannya di Bandung. Jadi orang Sunda bangga ? tentu saja. Orang Sunda ini salah satu yang tidak takluk dengan kerajaan terbesar di Nusantara loh. Dengan begitu apa sudah cukup bangga dengan diri sendiri ? Belum ! Masih banyak yang bisa saya pilih untuk saya sombongkan ! Saya anak Unpad, juga anak UI, fans AC Milan yang sudah berkali-kali menang Liga Champion Eropa, juga fans Persib yang juara beberapa tahun yang lalu ! daaaannn seterusnya. Dari situ kita bisa lihat, identitas itu ada yang diberikan Tuhan (Suku, tempat lahir dan tinggal), ada yang harus diraih (kampus-kampus, pekerjaan), namun ternyata ada juga yang bisa dipilih dengan seenaknya (klun sepak bola kesukaan). Dengan kata lain, identitas ini ada yang harus didapatkan dengan nasib, usaha, atau gratis.
Nah, sekarang, apa pentingnya identitas di masa sekarang ? Penting sekali. Sekarang, orang kerap kali membanggakan identitasnya. Akibat apa ? Macam-macam. Tapi yang paling mengena adalah globalisasi dan internet beserta turunan-turunannya. Globalisasi memberikan ruang informasi yang lebih luas untuk masyarakat. Masyarakat menjadi paham bahwa ada banyak identitas lain yang selama ini tidak pernah mereka lihat. Selain itu, globalisasi juga “menuntut” kita untuk memiliki identitas agar kita memiliki tempat dalam globalitas dunia.
Agar tidak terlalu berkembang, saya coba gambarkan secara langsung melalui sepak bola. Sebelum globalisasi dan internet (Globalization 3.0 kalau kata Friedman), masih jarang orang yang tahu tentang hooliganisme. Dulu, orang menonton sepak bola murni karena mereka cinta klub sepak bola itu, dan karena klub sepak bola itu datang dari tempat di mana mereka tinggal. Tentu inilah sewajar-wajarnya orang menyukai sebuah klub sepak bola. Namun lama kelamaan, makin banyak “aturan” untuk menyukai klub sepak bola. Misal, untuk jadi fans sejati, maka harus datang ke stadion. Atau, untuk menjadi fans yang keren, maka harus menjalani hooliganisme.
Hooliganisme sendiri dimulai di Inggris, dan di Inggris sekalipun Hooligan adalah kelompok yang dibenci para penikmat sepak bola Inggris. Kalau pernah menonton film Green Street Hooligan (2005), bisa dilihat bagaimana para Hooligan ini memiliki kebanggaan tersendiri ketika mereka berhasil menghajar fans dari klub sepak bola lain. Bagi saya ini konyol, dan walaupun datang dari Inggris, negara yang lebih maju dan memang lebih keren, ya tidak perlu ditiru karena tidak ada gunanya. Namun perbedaannya begini: di Inggris, mereka sadar Hooliganisme tidak baik untuk perkembangan sepak bola mereka. Sepak bola di sana sudah mulai menjadi industri ketika Hooliganisme ramai. Ya di saat itu juga lah mereka mengerahkan berbagai macam cara untuk menghentikan Hooliganisme itu sendiri. Di sini ? Wah. Tiket ilegal masih banyak. Tidak usah dibahas dengan rinci, karena saya takut kena UU ITE. Hahaha.
Di sisi lain (dan bagi saya, di sisi inilah identitas akan banyak dibicarakan), ada sebuah kondisi masyarakat di mana identitas menjadi penting lagi. Entah kenapa, belakangan ini identitas menjadi sesuatu yang kembali krusial. Dugaan saya, ini muncul karena tekanan sosial. Manusia butuh kebanggaan agar ia merasa diterima di dalam masyarakatnya. Ketika mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang membanggakan secara positif dengan kapabilitasnya yang terbatas, maka mereka mencari pelampiasan dengan mencari identitas lain. Salah satunya ya itu, Hooliganisme, gebukin orang, lalu bangga.
Krisis identitas adalah sebuah konsep yang akrab dengan masyarakat dewasa ini. Orang yang merasakan krisis identitas akan mencoba mencari identitas seperti apa yang cocok dengan mereka, lalu di manakah mereka akan memiliki tempat di sebuah kelompok masyarakat. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi, identitas itu kalau bukan nasib, kemampuan, ya gratisan. Salah satu yang gratisan adalah dengan menjadi fans sepak bola. Tidak bisa bayar tiket ? Pakai cara ilegal. Ingin menonjol di antara kawan-kawan ? Gebukin orang, lalu masukkan ke akun media sosial. Dengan cara seperti itulah mereka memenuhi krisis identitas mereka.
Di sini, peran media sosial sangatlah dahsyat. Banyak orang yang haus akan eksistensi di media sosial. Mereka akan melakukan apa saja demi mendapatkan pengakuan dari kelompok masyarakatnya melalui media sosial. Mungkin saya termasuk dengan menulis tulisan ini. Tapi entahlah, jujur, niat saya menulis ini hanya untuk curhat. Tentu ada rasa bangga ketika kita membagikan sesuatu di media sosial, orang lain mengomentari dengan positif bak gayung bersambut. Namun kembali, ketika tidak bisa menyuarakan sesuatu yang positif karena yang positif itu “wow factor” dan kadar “berbeda”-nya kurang, lebih mudah melakukan sesuatu yang negatif. Kembali, gebukin orang yang dianggap musuh oleh kelompok masyarakat di mana mereka adalah anggotanya.
Padahal, kalau mau menjadi terkenal di media sosial tidaklah begitu sulit kalau kamu kreatif. Banyak Bobotoh maupun Jakmania yang mampu menonjol dengan ciri khas masing-masing. Entah itu ada yang pakai baju pocong, pakai baju seperti Syekh Puji, atau mungkin pakai topeng macan seperti Tiger Mask, itu akan menjadi sesuatu yang unik dan menjadi sorotan. Membanggakan kan ?
Kondisi yang seperti ini menjadikan rivalitas Bobotoh dan Jakmania menjadi sesuatu yang mengerikan, membahayakan. Tentu zaman tidak bisa disalahkan sepenuhnya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ini hanyalah salah satu faktor. Masih ada faktor lain yang harus diperhitungkan, seperti bagaimana para gegedug yang kekeuh agar permusuhan ini dipelihara, namun kurang memperhatikan bagaimana “di bawah” permusuhan ini seringkali dibumbui oleh cerita-cerita yang tidak sepenuhnya benar dan bersifat provokatif.
Melihat Heru Joko dan Ferry Indra Syarif yang makin mesra tentu memberikan angin segara kepada Bobotoh dan Jakmania yang ingin berdamai. Saya juga mulai melihat beberapa pentolan Viking mulai membuat tulisan-tulisan yang intinya menyatakan bahwa mereka sudah lelah dengan permusuhan ini. Di twitter –ladangnya adu omong kasar dan pamer gebukin orang, makin banyak Bobotoh dan Jakmania yang menyuarakan keinginan untuk damai.
Namun tentunya, ini tidak akan semudah itu. Bukan hanya Heru Joko dan Ferry Indra Syarif yang harus menyuarakan perdamaian, namun para gegedug legenda supporter dari kedua kubu harus ikut bersuara. Kordinator-kordinator di lapangan terutama. Saya tidak bisa menyebut nama karena jujur saja saya tidak tahu. Namun saya membayangkan, tentu ada kelompok-kelompok kecil di dalam Bobotoh (dan Viking) juga Jakmania yang mengorganisir dalam skala yang lebih kecil. Mereka harus berani menindak anak buah atau anggotanya yang membuat masalah, mereka juga harus menjaga situasi kondusif di stadion. Begitu juga dengan aparat dan pihak panpel pertandingan. Screening tiket harus diperketat. Harus ada larangan bagi fans yang ketahuan masuk dengan cara ilegal. Larang mereka masuk lagi ke stadion. Kalau perlu seumur hidup, dan di seluruh stadion di Indonesia. Kalian tidak akan rugi kok dengan cara seperti itu.
Kita tidak akan bisa menahan laju globalisasi yang sudah bak Juggernaut menghancurkan sana sini. Namun tentunya, kita bisa melindungi diri kita sendiri dan klub kesayangan kita agar tidak menjadi korban dari kegilaan zaman. Jadilah fans yang bermartabat. Jadikan mereka yang tewas atas nama rivalitas sebagai pengingat bahwa sepak bola ada untuk dinikmati bersama. Hingga suatu saat, ketika bertemu Ricko, Rangga, Harun, Gilang, dan yang lain yang sudah mendahului, kita semua masih punya wajah untuk “laporan” kepada mereka.


